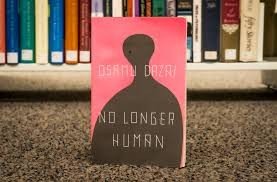Oleh: M. Reza Adhitya (Pemerhati Seni dan Film Animasi)
Sekilas, Look Back (2024) tampak sebagai film animasi yang lembut dan personal, kisah dua gadis muda yang mencintai dunia menggambar dan menemukan persahabatan melalui seni. Namun, di balik visual yang tenang dan narasi yang sederhana, film ini menyimpan kritik sosial yang halus tetapi menggugah: bagaimana bakat anak muda sering kali berubah menjadi beban, bahkan bentuk eksploitasi yang tak disadari, akibat ekspektasi lingkungan di sekitarnya.
Film ini diadaptasi dari karya Tatsuki Fujimoto, kreator yang dikenal berani mengeksplorasi sisi rapuh manusia. Dalam Look Back, Fujimoto tidak menampilkan kekerasan atau absurditas ekstrem seperti karya-karyanya yang lain. Ia memilih pendekatan sunyi, dan justru karena itu, pesannya terasa lebih menghantam. Film ini mengajak penonton menengok bagaimana pujian, perbandingan, dan tuntutan yang tampak “positif” dapat menekan jiwa kreatif anak-anak.
Tokoh Fujino dan Kyomoto menjadi pusat ketegangan emosional tersebut. Fujino digambarkan sebagai anak yang percaya diri, populer di sekolah berkat komik stripnya, dan terbiasa menerima pengakuan. Menggambar adalah kesenangan hingga suatu hari ia berhadapan dengan karya Kyomoto. Dalam sekejap, rasa bangga berubah menjadi kecemasan. Bakat yang sebelumnya menyenangkan kini terasa seperti sesuatu yang harus dipertahankan. Pujian yang dulu menguatkan, pelan-pelan menjelma tekanan untuk selalu unggul.
Sementara itu, Kyomoto menghadirkan sisi lain dari problem yang sama. Ia berbakat luar biasa, tetapi hidup dalam isolasi. Ia jarang hadir di sekolah, menghabiskan hari-harinya sendirian di kamar, menggambar tanpa henti. Lingkungannya mengagumi hasil karyanya, namun nyaris tak mengenal sosok di balik goresan itu. Look Back tidak meromantisasi kesendirian ini. Film ini justru menunjukkan bahwa bakat, ketika tidak diimbangi perhatian emosional, dapat menjadi sangkar. Kyomoto bukan hanya seniman muda berbakat; ia juga anak yang rapuh, kesepian, dan kesulitan menemukan tempat di dunia sosialnya.
Yang paling mengusik adalah bagaimana kedua tokoh ini memikul tanggung jawab yang nyaris setara dengan seniman profesional, padahal mereka masih remaja. Tidak ada figur otoritas yang secara eksplisit memaksa. Eksploitasi di sini bekerja secara halus melalui pujian, perbandingan, dan ekspektasi diam-diam. Fujino dan Kyomoto mulai percaya bahwa nilai diri mereka ditentukan oleh seberapa banyak dan seberapa baik mereka menghasilkan karya. Seni tidak lagi menjadi ruang bermain dan tumbuh, melainkan tolok ukur harga diri.
Tragedi yang kemudian terjadi terasa begitu menyakitkan karena fondasi emosionalnya telah dibangun dengan sabar. Rasa bersalah Fujino setelahnya terasa nyata dan manusiawi. Ia menyalahkan dirinya atas hal-hal yang berada di luar kendalinya, sebuah refleksi tentang bagaimana seniman muda kerap menginternalisasi beban yang seharusnya tidak mereka tanggung. Dalam duka itu, Look Back memperlihatkan betapa rapuhnya identitas anak-anak yang tumbuh dengan keyakinan bahwa bakat adalah segalanya.
Lebih dari sekadar kisah tentang seni dan persahabatan, Look Back adalah pengingat yang lembut namun tegas. Di balik setiap bakat luar biasa, ada anak yang membutuhkan waktu, ruang, dan perlindungan. Film ini mengajak kita sebagai orang tua, pendidik, dan masyarakat, untuk berhenti sejenak dan bertanya: apakah kita merawat bakat, atau justru membebani pemiliknya?
Look Back tidak menolak apresiasi terhadap talenta. Ia hanya mengingatkan bahwa kreativitas tidak boleh tumbuh dengan mengorbankan kesehatan emosional. Briliasi sejati seharusnya berjalan seiring dengan kesejahteraan. Dan mungkin, seperti yang disiratkan film ini, hal paling manusiawi yang bisa kita lakukan adalah membiarkan anak-anak bertumbuh dengan ritme mereka sendiri tanpa harus selalu menjadi luar biasa.