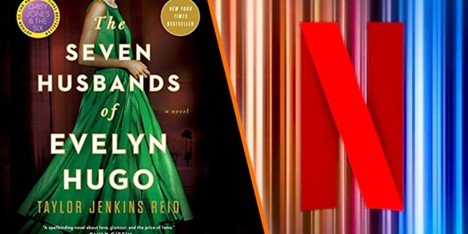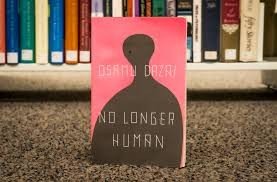Oleh: Kanaya Ratu Vanisa (Pemerhati Novel dan Isu Sastra Populer)
Banyak pembaca mendekati The Seven Husbands of Evelyn Hugo sebagai kisah cinta glamor yang dibalut tragedi. Hollywood, gaun mahal, dan kehidupan selebritas menjadi daya tarik utama novel ini. Namun, semakin jauh kisah Evelyn Hugo dibaca, semakin jelas bahwa cerita tersebut bukan sekadar hiburan. Novel ini bekerja sebagai cermin yang memantulkan realitas pahit tentang bagaimana perempuan hidup, bernegosiasi, dan bertahan di dalam sistem kekuasaan yang timpang.
Dalam novel The Seven Husbands of Evelyn Hugo (2017), Taylor Jenkins Reid menggunakan Hollywood sebagai panggung untuk memperlihatkan politik seksualitas yang bekerja secara halus, tetapi kejam. Relasi antara laki-laki dan perempuan dalam novel ini tidak pernah netral. Sejalan dengan gagasan Kate Millett dalam Sexual Politics (1970), hubungan intim di dunia Evelyn bukan sekadar persoalan perasaan, melainkan arena politik tempat kekuasaan dipertaruhkan. Tubuh, cinta, dan bahkan identitas menjadi bagian dari negosiasi yang sarat kepentingan.
Sejak awal memasuki industri hiburan, Evelyn diposisikan bukan sebagai subjek, melainkan objek. Ia “dibentuk” oleh sistem: warna kulitnya diputihkan, namanya diubah, penampilannya diatur, dan tubuhnya dikontrol demi memenuhi standar Hollywood yang patriarkal dan berorientasi pada selera laki-laki. Dalam kerangka politik seksualitas, ini merupakan bentuk kolonisasi tubuh perempuan. Evelyn hanya bisa bertahan sejauh ia mampu menyesuaikan diri dengan tatapan maskulin yang mendominasi industri tersebut.
Tujuh pernikahan Evelyn sering dibaca sebagai kegagalan romantis atau cerminan karakter yang tidak stabil. Namun, pembacaan semacam itu justru menutup dimensi politik dari pilihan-pilihannya. Pernikahan dalam novel ini berfungsi sebagai instrumen kekuasaan. Ketika akses perempuan terhadap otoritas dan posisi strategis dibatasi, Evelyn menggunakan pernikahan sebagai satu-satunya jalur yang tersedia untuk memperoleh perlindungan, pengaruh, dan kendali atas hidupnya sendiri. Setiap suami hadir dengan fungsi tertentu: ada yang mendongkrak karier, ada yang menjaga citra publik, dan ada pula yang menyembunyikan kebenaran tentang seksualitasnya. Pernikahan, dalam konteks ini, bukan ruang cinta, melainkan transaksi.
Dimensi politik tersebut semakin kentara ketika membahas relasi Evelyn dengan Celia St. James. Kebutuhan untuk menyembunyikan hubungan sesama jenis ini menunjukkan bagaimana heteroseksualitas dipaksakan sebagai norma. Pemikiran Judith Butler dan Eve Kosofsky Sedgwick tentang heteroseksualitas wajib menemukan relevansinya di sini. Dalam sistem patriarki, nilai perempuan ditentukan oleh ketersediaannya bagi laki-laki. Hubungan lesbian menjadi ancaman karena mengeluarkan perempuan dari ekonomi hasrat laki-laki. Karena itu, seksualitas Evelyn tidak hanya bersifat personal, tetapi juga politis dan berbahaya.
Ironi terbesar dari kisah Evelyn terletak pada keberhasilannya. Ia menjadi figur yang tampak berkuasa, mampu memanipulasi sistem dan para laki-laki di sekitarnya. Namun, kekuasaan itu selalu bersyarat. Ia hanya bisa menang dengan terus memainkan peran, menekan identitas sejatinya, dan menukar kejujuran dengan keamanan. Kemenangan Evelyn bukanlah kebebasan, melainkan bentuk bertahan hidup yang mahal. Identitasnya, sebagai perempuan, sebagai kekasih, sebagai manusia, terus menjadi medan konflik.
Di titik inilah novel ini terasa begitu relevan. The Seven Husbands of Evelyn Hugo mengingatkan bahwa politik seksualitas bukan konsep abstrak dalam buku teori. Ia hadir dalam kehidupan sehari-hari perempuan: dalam cara tubuh dinilai, dalam pilihan hidup yang dibatasi, dan dalam cinta yang harus disembunyikan. Hollywood dalam novel ini hanyalah metafora dari sistem yang lebih luas, sistem yang masih sering menempatkan perempuan sebagai objek yang harus diatur, dikendalikan, dan dipoles agar sesuai dengan kepentingan kekuasaan.
Lebih dari kisah tentang ketenaran, novel ini adalah kritik sosial yang tajam. Ia mengajak pembaca melihat bahwa selama nilai perempuan masih ditentukan oleh sistem yang patriarkal, identitas perempuan, baik di ruang publik maupun privat, akan selalu menjadi arena politik. Evelyn Hugo bukan hanya tokoh fiksi; ia adalah representasi dari banyak perempuan yang belajar bertahan di dunia yang sejak awal tidak dirancang untuk mereka menang.