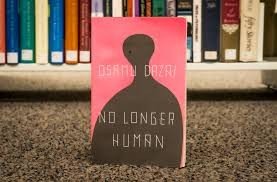Oleh: Rizqi Apsarah (Mahasiswa, Pemerhati Gender Studies)
Film kerap dipahami sebagai sarana hiburan, padahal ia juga berfungsi sebagai medium refleksi sosial. Melalui narasi dan visual, film mampu mengajak penonton meninjau kembali nilai-nilai yang selama ini dianggap wajar dan tak perlu dipertanyakan. Mulan menjadi contoh menarik bagaimana sebuah kisah populer dapat dibaca sebagai kritik halus terhadap konstruksi identitas, gender, dan ekspektasi budaya. Cerita tentang seorang perempuan yang menyamar sebagai prajurit bukan semata kisah heroik, melainkan cermin pergulatan individu dengan norma sosial yang membatasi.
Berangkat dari legenda Tiongkok tentang Hua Mulan, film ini mengisahkan seorang anak perempuan yang menggantikan ayahnya pergi berperang demi menjaga kehormatan keluarga. Namun, konflik utama dalam Mulan tidak berhenti pada pengorbanan fisik atau loyalitas terhadap negara. Konflik yang lebih dalam justru hadir dalam bentuk pertarungan batin, yakni ketika Mulan harus menekan identitasnya sendiri agar dapat bertahan dalam sistem yang hanya mengakui laki-laki sebagai simbol kekuatan dan kehormatan.
Dalam perspektif teori identitas sosial yang dikemukakan oleh Erik Erikson, individu membentuk jati diri melalui interaksi antara dorongan personal dan tuntutan lingkungan. Mulan berada pada titik krisis identitas tersebut. Di satu sisi, ia dibesarkan dalam budaya yang menuntut perempuan untuk patuh, tenang, dan berada di ruang domestik. Di sisi lain, ia memiliki keberanian, kecerdikan, dan kapasitas kepemimpinan yang tidak sesuai dengan peran gender yang dilekatkan padanya. Penyamaran Mulan sebagai prajurit laki-laki menjadi strategi bertahan hidup, sekaligus simbol keterasingan dari diri sendiri.
Peperangan dalam film ini dapat dibaca melalui kacamata simbolik. Konflik bersenjata yang ditampilkan bukan hanya pertarungan antara dua kubu, tetapi juga representasi dari konflik internal Mulan. Ia terus berada dalam dilema antara mengikuti aturan sosial atau menerima dirinya secara utuh. Identitas yang ia sembunyikan menjadi beban psikologis, tetapi juga sumber kekuatan. Di sinilah film menegaskan bahwa keberanian tidak selalu lahir dari kepatuhan, melainkan dari kesadaran akan siapa diri kita sebenarnya.
Isu gender menjadi pusat penting dalam pembacaan Mulan. Dalam kerangka teori feminisme liberal, sebagaimana dirumuskan oleh Betty Friedan, ketidaksetaraan gender bukan disebabkan oleh ketidakmampuan perempuan, melainkan oleh sistem sosial yang membatasi pilihan dan ruang gerak mereka. Mulan tidak menolak budayanya secara frontal, tetapi menantang interpretasi sempit terhadap tradisi. Ia membuktikan bahwa nilai kehormatan, loyalitas, dan keberanian tidak melekat pada jenis kelamin tertentu. Dengan cara ini, film tidak memposisikan tradisi sebagai musuh, melainkan sebagai ruang yang dapat dinegosiasikan dan dimaknai ulang.
Menariknya, Mulan juga tidak menggambarkan keberhasilan tokohnya sebagai hasil dari kekuatan fisik semata. Keberhasilan Mulan justru muncul dari kejujuran, kecerdikan, dan empati. Hal ini sejalan dengan kritik terhadap maskulinitas hegemonik yang selama ini mendominasi narasi kepahlawanan. Film ini menawarkan definisi kepahlawanan yang lebih inklusif, di mana keberanian berarti bertanggung jawab atas pilihan hidup dan berani menghadapi konsekuensinya.
Relevansi Mulan terasa kuat dalam kehidupan modern, ketika banyak individu harus berhadapan dengan ekspektasi sosial yang kaku. Tekanan untuk menyesuaikan diri sering kali membuat seseorang mengorbankan kejujuran terhadap dirinya sendiri. Melalui kisah Mulan, film ini mengingatkan bahwa konflik antara identitas personal dan tuntutan sosial bukanlah kelemahan, melainkan bagian dari proses menjadi manusia.
The last but not least, Mulan dapat dibaca sebagai narasi tentang keberanian yang melampaui medan perang. Keberanian itu hadir dalam bentuk kesediaan untuk mengenali diri, menegosiasikan nilai budaya, dan memperluas makna kehormatan. Film ini menunjukkan bahwa menjadi pahlawan tidak selalu berarti menaklukkan musuh, tetapi sering kali berarti berani berdiri sebagai diri sendiri di tengah dunia yang menuntut keseragaman.