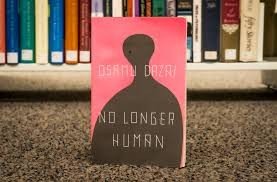Oleh: Hasna Kamilah (Pemerhati Budaya dan Film Studies)
Bayangkan sebuah robot terdampar di tengah hutan liar, dikelilingi pepohonan, sungai, dan hewan-hewan yang hidup berdasarkan naluri alam. Ia tidak memiliki emosi, tidak memahami bahasa alam, dan hanya bekerja mengikuti perintah pemrograman. Aneh? Bisa jadi. Namun, justru dari keanehan itulah The Wild Robot menawarkan refleksi mendalam tentang relasi manusia, teknologi, dan alam.
Film animasi produksi DreamWorks Animation ini diadaptasi dari novel Peter Brown (2016) dan disutradarai oleh Chris Sanders. Dirilis pada 2024, The Wild Robot bukan sekadar tontonan keluarga, melainkan alegori ekologis yang halus dan menyentuh. Kisahnya sederhana tetapi sarat makna: sebuah robot bernama Rozzum 7134 atau Roz harus belajar bertahan hidup di alam yang sama sekali asing baginya.
Pada awalnya, Roz tampil sebagai simbol teknologi modern yang kaku dan mekanis. Ia beroperasi murni berdasarkan logika dan perintah. Alam diperlakukannya sebagai lingkungan kerja yang harus “diselesaikan”, bukan sebagai ruang hidup yang perlu dipahami. Namun, hutan tidak tunduk pada algoritma. Untuk bertahan, Roz terpaksa menyesuaikan diri. Ia belajar mengamati, meniru, dan memahami makhluk hidup di sekitarnya. Perlahan, batas antara mesin dan empati mulai memudar.
Transformasi Roz semakin terasa melalui hubungannya dengan Brightbill, seekor anak angsa yang kehilangan keluarganya akibat insiden yang tidak disengaja. Bersama Fink, seekor rubah yang cerdik, Roz merawat Brightbill agar bisa bertahan hidup hingga musim migrasi tiba. Relasi ini bukan sekadar kerja sama fungsional, melainkan ikatan emosional. Di sinilah film ini berbicara lebih jauh: empati bukan monopoli makhluk biologis, melainkan hasil dari proses belajar dan kepedulian.
Puncak makna film ini muncul ketika musim dingin datang. Di tengah badai salju yang mengancam, Roz dan Fink membuka tempat berlindung bagi hewan-hewan lain. Mereka saling menjaga, berbagi ruang, dan bertahan bersama. Adegan ini menjadi metafora kuat tentang solidaritas ekologis—bahwa keselamatan satu makhluk terkait erat dengan keselamatan yang lain.
Kontras tajam muncul saat perusahaan pembuat Roz, Dynamic Universal, datang untuk “menarik kembali” aset mereka. Alih-alih memahami konteks alam, teknologi ditampilkan sebagai kekuatan destruktif: senjata ditembakkan, hutan terbakar, dan keseimbangan ekosistem terancam. Di titik ini, film dengan jelas mengambil sikap: teknologi tanpa kesadaran ekologis berpotensi merusak kehidupan.
Roz akhirnya menyadari dilema tersebut. Keputusannya untuk pergi bukanlah bentuk kekalahan, melainkan pengorbanan. Ia membantu memulihkan hutan sebelum pergi, memastikan ekosistem tetap bertahan. Meski kemudian diatur ulang, kenangan tentang alam dan makhluk hidup tetap melekat—sebuah isyarat bahwa pengalaman dan nilai tidak mudah dihapus begitu saja.
Melalui kisah Roz, The Wild Robot menegaskan bahwa teknologi pada dasarnya bersifat netral. Yang menentukan adalah cara manusia merancang, menggunakan, dan menempatkannya dalam kehidupan. Teknologi dapat menjadi ancaman jika berjalan tanpa empati, tetapi juga bisa menjadi mitra alam jika disertai kesadaran dan tanggung jawab.
Di tengah krisis iklim dan percepatan teknologi saat ini, film ini terasa relevan. The Wild Robot mengajak kita bertanya: apakah kita ingin teknologi yang menaklukkan alam, atau teknologi yang belajar hidup bersama alam? Jawabannya, seperti yang ditunjukkan Roz, bergantung pada pilihan dan tindakan kita sendiri.