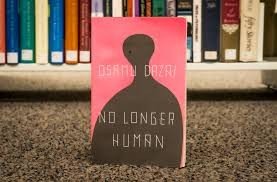Oleh: Firly Azkapida R. (Mahasiswa Sastra Inggris UNPAM)
Di tengah derasnya arus teknologi digital, cinta tak lagi hadir semata sebagai peristiwa personal. Ia kini dimediasi oleh layar, aplikasi, dan sistem yang bekerja tanpa henti membaca kebiasaan manusia. Novel Lovechitec karya Windy Joana H. menangkap kegelisahan zaman itu dengan cara yang tenang, tetapi tajam. Melalui kisah fiksi yang terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari, novel ini mengajak pembaca merenungkan bagaimana teknologi tidak hanya mengubah cara manusia berkomunikasi, tetapi juga memengaruhi cara mereka merasakan, memahami, dan mendefinisikan cinta.
Lovechitec tidak menyuguhkan romansa dalam pengertian klasik. Cinta di dalamnya bukan sekadar pertemuan dua hati, melainkan proses emosional yang berlangsung di tengah interaksi digital yang intens. Hubungan antartokohnya tumbuh melalui pesan singkat, respons cepat, dan kehadiran virtual yang nyaris tanpa jeda. Di titik inilah novel ini menjadi relevan: ia memperlihatkan bagaimana batas antara ketulusan perasaan dan ketergantungan emosional kian kabur.
Salah satu kekuatan utama Lovechitec terletak pada penggambaran konflik batin para tokohnya. Mereka mencintai, tetapi sekaligus ragu. Mereka merasa dekat, namun juga terasing. Teknologi menghadirkan ilusi keintiman, kehadiran yang terasa konstan, tetapi sering kali dangkal. Pembaca diajak melihat bagaimana cinta dapat tumbuh subur di ruang digital, sekaligus rapuh karena mudah disalahartikan sebagai kebutuhan untuk selalu terhubung.
Fenomena ini bukan sekadar persoalan fiksi. Ia mencerminkan realitas sosial, terutama di kalangan generasi muda yang tumbuh bersama teknologi. Ketika pesan tak segera dibalas, kecemasan muncul. Ketika interaksi daring berkurang, rasa kehilangan pun datang. Lovechitec menangkap kegelisahan itu tanpa menggurui, seolah berkata bahwa teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari relasi manusia dengan segala konsekuensinya.
Lebih jauh, Windy Joana H. secara halus mengangkat persoalan identitas di era digital. Para tokohnya dihadapkan pada dilema antara menjadi diri sendiri dan menyesuaikan diri dengan citra yang dibentuk teknologi. Identitas tidak lagi sepenuhnya personal, melainkan dipengaruhi oleh algoritma, aplikasi, dan ekspektasi sosial. Dalam dunia Lovechitec, manusia kerap menampilkan versi diri yang “terlihat baik” di layar, meski belum tentu jujur pada perasaan sendiri.
Di sinilah novel ini melampaui kisah cinta biasa. Lovechitec menjadi refleksi tentang pencarian jati diri di tengah sistem yang terus menuntut penyesuaian. Cinta dan identitas berjalan beriringan, sama-sama diuji oleh kehadiran teknologi yang menawarkan kemudahan sekaligus tekanan. Tokoh-tokohnya belajar bahwa mencintai orang lain sering kali menuntut keberanian untuk terlebih dahulu jujur pada diri sendiri.
Dari segi bahasa, Lovechitec ditulis dengan gaya yang ringan dan komunikatif. Dialog-dialognya terasa natural, dekat dengan percakapan sehari-hari, terutama bagi pembaca yang akrab dengan dunia digital. Alurnya berkembang secara bertahap, memberi ruang bagi pembaca untuk mengikuti pertumbuhan emosional para tokoh tanpa tergesa-gesa. Kesederhanaan ini justru menjadi kekuatan, karena memungkinkan gagasan-gagasan besar tentang cinta dan teknologi disampaikan dengan jernih.
Singkatnya, Lovechitec adalah novel yang menawarkan lebih dari sekadar kisah romantis. Ia hadir sebagai kritik sosial yang lembut terhadap ketergantungan manusia pada teknologi. Novel ini mengingatkan bahwa secanggih apa pun sistem yang diciptakan, cinta tetap membutuhkan kejujuran, empati, dan kehadiran nyata. Dalam keseimbangan antara romansa dan refleksi sosial itulah Lovechitec menemukan relevansinya sebagai cermin kecil bagi masyarakat modern yang sedang belajar mencintai di tengah algoritma.