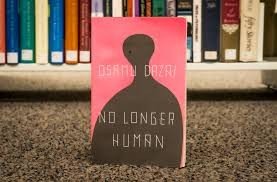Oleh: Syifa Aulia Maharoh (Penikmat Film dan Karya Sastra)
Ketika mendengar judul Beauty and the Beast, banyak orang spontan membayangkan dongeng anak-anak atau film musikal Disney dengan akhir bahagia yang nyaris klise. Cerita ini kerap dianggap ringan, sederhana, dan tidak menuntut pembacaan yang serius. Namun, jika ditelisik lebih jauh, Beauty and the Beast justru menyimpan lapisan makna yang membuatnya tetap relevan sebagai karya sastra popular terutama dalam cara ia merefleksikan kecenderungan manusia menilai orang lain, membangun relasi, dan mengalami perubahan diri.
Salah satu aspek paling menonjol dari cerita ini adalah bagaimana penampilan fisik memengaruhi perlakuan sosial. Sosok Beast sejak awal langsung dicap sebagai makhluk menakutkan semata-mata karena rupanya. Ia tidak diberi ruang untuk dipahami lebih jauh, apalagi dipercaya. Penilaian instan ini terasa sangat dekat dengan realitas hari ini, ketika banyak orang masih menakar nilai seseorang dari tampilan luar, status sosial, atau kesan pertama. Dalam konteks tersebut, Beauty and the Beast tidak terasa sebagai cerita lama, melainkan cermin yang memantulkan kebiasaan sosial yang belum banyak berubah.
Kehadiran tokoh Belle juga menjadi alasan mengapa kisah ini tetap relevan bagi pembaca dan penonton modern. Belle digambarkan sebagai perempuan yang berbeda dari lingkungannya. Ia gemar membaca, berpikir kritis, dan tidak sepenuhnya tunduk pada standar sosial desa tempat ia tinggal. Dalam banyak hal, Belle merepresentasikan individu yang merasa “tidak cocok” dengan lingkungannya, tetapi tetap memilih setia pada dirinya sendiri. Kemandirian Belle tidak ditampilkan secara demonstratif, melainkan lewat pilihan-pilihan kecil yang terasa realistis dan membumi.
Relasi cinta dalam Beauty and the Beast pun dibangun dengan cara yang relatif manusiawi. Belle tidak serta-merta jatuh cinta pada Beast. Perasaan itu tumbuh perlahan, seiring dengan proses saling mengenal, memahami, dan berubah. Cinta tidak digambarkan sebagai kilatan emosi sesaat, melainkan sebagai perjalanan emosional yang menuntut empati dan kesabaran. Dalam lanskap kisah romantis populer yang sering menekankan cinta instan, pendekatan ini terasa lebih jujur dan relevan.
Memang, tidak sedikit kritik yang diarahkan pada cerita ini. Sebagian pembaca dan penonton menilai Beauty and the Beast berpotensi menormalisasi relasi yang tidak sehat, terutama pada fase awal hubungan Belle dan Beast. Kritik tersebut layak diperhatikan. Namun, jika dibaca secara lebih utuh, inti cerita ini justru terletak pada pertumbuhan pribadi. Beast tidak “dibenarkan” dalam sikap kasarnya. Ia justru harus berubah, belajar mengendalikan emosi, menghormati orang lain, dan melepaskan egonya, sebelum layak menerima cinta. Pesan ini penting: cinta seharusnya tidak menjadi pembenaran atas perilaku buruk, melainkan dorongan untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
Relevansi Beauty and the Beast semakin tampak melalui adaptasi film live-action tahun 2017 yang disutradarai oleh Bill Condon. Versi ini menghadirkan pendekatan yang lebih modern, terutama dalam penggambaran Belle sebagai perempuan yang lebih vokal, mandiri, dan berani menyuarakan pendapat. Adaptasi tersebut menunjukkan bahwa karya sastra populer dapat terus hidup dengan menyesuaikan diri pada nilai dan perspektif zamannya, tanpa harus kehilangan pesan moral utama.
Sebagai karya populer, Beauty and the Beast memang tidak menawarkan kompleksitas filsafat yang rumit. Namun, justru dalam kesederhanaannya itulah kekuatannya terletak. Cerita ini mengajak pembaca dan penonton untuk mempertanyakan kebiasaan menilai orang lain dari permukaan, serta mengingatkan bahwa perubahan diri adalah proses yang mungkin tetapi membutuhkan usaha dan kesadaran.
Beauty and the Beast bukan sekadar dongeng tentang cinta yang menang atas segalanya. Ia adalah kisah tentang bagaimana manusia belajar melihat melampaui rupa, mengelola luka dan ego, serta tumbuh melalui relasi yang penuh tantangan. Di balik balutan musik dan fantasi, cerita ini menyimpan refleksi yang tetap relevan: bahwa memahami orang lain sering kali dimulai dari keberanian untuk menunda penilaian, dan memberi ruang bagi perubahan.