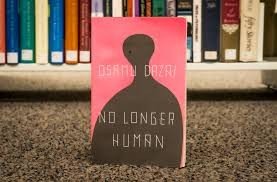Oleh: Bayu Saputra (Pemerhati Sastra Klasik)
Sastra kerap berfungsi sebagai cermin penderitaan manusia, bukan untuk menghakimi, melainkan untuk memahami. Cerita pendek The Black Cat karya Edgar Allan Poe adalah contoh kuat bagaimana luka psikologis berkelindan dengan realitas sosial, lalu berujung pada kehancuran moral. Melalui narasi orang pertama yang intens, Poe menampilkan keruntuhan batin seorang tokoh tanpa nama, sekaligus memperlihatkan bagaimana trauma yang tak terselesaikan dapat bermetamorfosis menjadi kekerasan.
Kisah ini berpusat pada seorang narator yang perlahan tenggelam dalam kegilaan dan kebrutalan, terutama terhadap hewan dan istrinya. Namun, Poe tidak menyajikan kekerasan sebagai sifat bawaan yang lahir dari “kejahatan murni”. Ia menempatkannya sebagai akibat dari akumulasi trauma, kecanduan alkohol, dan keterasingan sosial. Dengan cara ini, The Black Cat menggeser fokus dari pelaku semata ke sistem dan kondisi yang membentuk perilakunya.
Isu sosial yang paling menonjol dalam cerita ini adalah alkoholisme. Alkohol hadir bukan sekadar latar, melainkan pemicu dan penanda rapuhnya mekanisme koping tokoh. Sang narator berulang kali mengaitkan dorongan agresifnya dengan konsumsi alcohol, sebuah cara melarikan diri dari tekanan batin yang tak mampu ia artikulasikan. Dalam konteks sosial abad ke-19, kondisi ini mencerminkan minimnya pemahaman dan empati terhadap kesehatan mental. Distres emosional sering diabaikan atau distigmatisasi; akibatnya, kecanduan menjadi pelarian yang justru memperparah kehancuran diri.
Kekejaman narator terhadap kucingnya, Pluto, dapat dibaca sebagai simbol trauma yang teralihkan. Hewan dan ruang domestic yang lazimnya diasosiasikan dengan rasa aman justru menjadi sasaran kekerasan. Di sini terlihat keruntuhan batas moral dan emosional. Tindakan brutal itu bukan sekadar sadisme, melainkan ekspresi rasa bersalah yang ditekan dan kebutuhan semu untuk menguasai sesuatu di tengah ketidakstabilan batin. Poe menyiratkan bahwa trauma yang direpresi, alih-alih dihadapi, dapat mengikis empati dan menormalkan kebrutalan.
Aspek lain yang tak kalah penting adalah isolasi. Sang narator semakin menjauh dari relasi sosial, keluarga, dan tanggung jawab moral. Ketidakmampuannya berkomunikasi atau mencari pertolongan menunjukkan lingkungan sosial yang miskin sistem dukungan. Isolasi ini mempercepat spiral kehancuran, sebuah pengingat bahwa trauma memburuk ketika penderita dibiarkan sendirian dengan lukanya. Tanpa ruang aman untuk berbagi, penderitaan bertransformasi menjadi tindakan destruktif.
Pilihan sudut pandang orang pertama membuat pembaca terperangkap dalam logika tokoh sekaligus menyaksikan rasionalisasi yang rapuh. Di sinilah kejeniusan Poe bekerja: kegilaan tidak ditampilkan sebagai sebab, melainkan konsekuensi. Narator terus berusaha membenarkan tindakannya, seolah dunia luar bersalah atas kehancurannya. Namun, di balik pembelaan diri itu, pembaca melihat jaringan sebab-akibat yang jelas: trauma yang diabaikan, kecanduan yang tak tertangani, dan keterasingan yang mengeras menjadi kekerasan.
Sebagai teks sastra, The Black Cat melampaui horor sensasional. Ia adalah komentar sosial yang gelap tentang kegagalan kolektif dalam mengenali dan merawat kesehatan mental. Poe tidak menawarkan solusi mudah atau akhir yang menenangkan. Sebaliknya, ia memaksa pembaca menatap dampak sosial dari pengabaian bagaimana penderitaan personal, ketika tidak direspons, dapat meluber menjadi bahaya bagi orang lain.
The Black Cat mengajak refleksi yang relevan lintas zaman: trauma bukan sekadar urusan individu, melainkan persoalan sosial. Ketika masyarakat gagal menyediakan empati, pemahaman, dan dukungan, luka batin dapat merusak identitas dan relasi, bahkan memantik kekerasan. Dengan membingkai kegilaan sebagai akibat, Poe menegaskan tanggung jawab kolektif untuk mendengar, merawat, dan mencegah kehancuran sebelum terlambat.