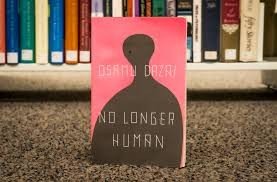Oleh: Auliana Puri A (Pemerhati Gender dan Budaya Populer)
Pada pandangan pertama, Barbie tampil sebagai film berwarna cerah dengan humor ringan dan dunia imajinatif yang menyenangkan. Namun, di balik estetika pop dan nuansa komedi, film yang disutradarai Greta Gerwig ini menyimpan kritik sosial yang tajam tentang ekspektasi gender dan pembentukan identitas perempuan. Barbie bukan sekadar hiburan, melainkan refleksi tentang bagaimana masyarakat menetapkan standar, menilai nilai diri, dan merespons perempuan ketika mereka keluar dari kerangka ideal yang ditentukan.
Di Barbieland, tokoh Barbie digambarkan sebagai figur sempurna: percaya diri, cantik, sukses, dan selalu positif. Ia dikagumi bukan hanya karena siapa dirinya, tetapi karena sejauh mana ia memenuhi gambaran ideal perempuan. Masalah muncul ketika Barbie mulai merasakan keraguan, kecemasan, dan ketidaksempurnaan. Pada titik ini, sistem yang sebelumnya memujanya justru menolaknya. Perubahan ini mengungkap mekanisme sosial yang akrab: perempuan sering dihargai selama mereka tampil “sempurna”, namun kehilangan tempat ketika menunjukkan kerentanan.
Krisis identitas Barbie dapat dibaca melalui gagasan Simone de Beauvoir yang menyatakan bahwa perempuan “tidak dilahirkan, melainkan menjadi” (1949). Identitas Barbie sejak awal telah dirancang, ia bukan subjek yang bebas menentukan makna hidupnya sendiri, melainkan simbol dari konstruksi sosial tentang perempuan ideal. Ketika ia mulai mempertanyakan tujuan dan jati dirinya, Barbie mengalami keterasingan. Situasi ini mencerminkan pengalaman banyak perempuan di dunia nyata: didorong untuk kuat dan berprestasi, tetapi jarang diberi ruang untuk ragu, rapuh, atau sekadar tidak tahu arah.
Ketegangan film semakin terasa ketika Barbie memasuki dunia nyata. Di sana, ia berhadapan dengan seksisme, objektifikasi, dan sikap meremehkan dari laki-laki. Adegan-adegan ini tidak disajikan secara didaktis, melainkan melalui satire yang tajam. Di sinilah kritik sosial film bekerja efektif: memperlihatkan bahwa di balik wacana pemberdayaan, relasi kuasa patriarkal masih membentuk interaksi sehari-hari. Sejalan dengan pemikiran Kate Millett tentang politik seksual, film ini menegaskan bahwa relasi gender tidak pernah sepenuhnya personal; ia dibentuk oleh struktur kekuasaan yang mengatur siapa yang didengar dan siapa yang diabaikan.
Menariknya, Barbie tidak menawarkan jawaban sederhana. Film ini tidak menutup cerita dengan pencapaian kesempurnaan baru, melainkan dengan pilihan untuk menerima ketidakpastian. Keputusan Barbie untuk merangkul ketidaksempurnaan dan ambiguitas menjadi simbol kebebasan yang lebih autentik. Pemberdayaan, menurut film ini, bukan soal memenuhi standar baru yang tak kalah menekan, melainkan memiliki otonomi untuk mendefinisikan diri sendiri.
Kekuatan Barbie terletak pada kemampuannya menjembatani kritik serius dengan bahasa populer. Humor dan visual yang atraktif membuat pesan film dapat menjangkau audiens luas tanpa kehilangan kedalaman. Ia mengajak penonton baik perempuan maupun laki-laki untuk mempertanyakan ekspektasi yang selama ini dianggap wajar. Mengapa perempuan harus selalu kuat tanpa boleh lelah? Mengapa keraguan sering dibaca sebagai kegagalan?
Sebagai karya budaya populer, Barbie menunjukkan bahwa film arus utama dapat menjadi medium refleksi sosial yang efektif. Ia tidak menolak feminitas, tetapi menantang definisinya yang sempit. Dengan menempatkan identitas sebagai proses, bukan hasil akhir, film ini mengingatkan bahwa menjadi manusia, dengan segala kekurangan dan pertanyaannya, lebih bernilai daripada sekadar menjadi ideal.
Barbie (2023) bukan hanya tentang boneka ikonik yang hidup, melainkan tentang perempuan yang belajar merebut kembali hak paling mendasar: hak untuk menentukan siapa dirinya. Di tengah dunia yang gemar memberi label dan standar, film ini mengajak kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah kita hidup untuk memenuhi ekspektasi, atau untuk menjadi diri sendiri?