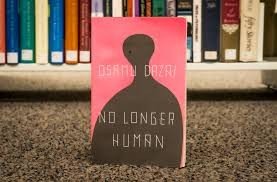Oleh: Tasya Aulia Hidayati (Pemerhati Sastra dan Budaya Populer)
Ketika pertama kali dirilis, Crazy Rich Asians kerap dibaca sebagai perayaan: komedi romantis yang gemerlap, pesta pernikahan mewah, dan momen representasi Asia yang lama dinantikan di panggung global. Namun, di balik kilau kemewahan dan humor ringan, film ini menyimpan ketegangan yang lebih sunyi dan mengusik. Ia mengajak penonton menatap satu pertanyaan lama yang tak pernah benar-benar usai: apa yang terjadi ketika cinta dinilai bukan dari komitmen, melainkan dari asal-usul keluarga dan kelas sosial?
Tokoh Rachel Chu hadir sebagai sosok yang, dalam narasi meritokrasi modern, patut dikagumi. Ia terdidik, mandiri, dan mapan secara finansial hasil dari kerja keras, bukan warisan. Namun, begitu Rachel melangkah ke lingkar elit keluarga Nick Young, prestasi itu seakan menguap. Penilaian yang ia terima jarang disampaikan secara frontal. Ia datang melalui percakapan sopan, perbandingan halus, dan ekspektasi tak terucap yang tak pernah ia sepakati. Ketimpangan disamarkan sebagai tradisi; eksklusi dibungkus sebagai kewajaran.
Dinamika ini selaras dengan pandangan Max Weber, yang menegaskan bahwa posisi sosial tidak hanya ditentukan oleh kekayaan, tetapi juga oleh status dan kekuasaan. Rachel mungkin memiliki pendidikan dan kemandirian ekonomi, tetapi ia tidak membawa “kehormatan sosial” yang diwariskan, sesuatu yang dijaga ketat oleh keluarga Nick. Sosok Eleanor Young, ibu Nick, memegang otoritas simbolik untuk menentukan siapa yang pantas diterima. Di sini, akses ke ruang elit bergantung lebih pada silsilah dan reputasi ketimbang kualitas personal.
Logika serupa bekerja di banyak konteks, termasuk di Indonesia, melalui konsep “sepadan” atau “setara”. Istilah-istilah ini sering dipakai untuk menilai kecocokan pasangan berdasarkan latar keluarga, pendidikan, dan status sosial. Sekilas tampak praktis, bahkan masuk akal. Namun, di baliknya, perhatian bergeser dari karakter dan nilai personal menuju posisi yang diwariskan. Ketika relasi disaring lewat kriteria kesetaraan sosial, pilihan individual pun terbatasi oleh standar yang mengistimewakan asal-usul di atas pengalaman hidup.
Pola ini meluas ke dunia pendidikan dan profesional. Lulusan sekolah tertentu atau mereka yang memiliki jaringan keluarga mapan kerap diasumsikan lebih “layak”, sementara yang lain harus terus-menerus membuktikan diri meski kualifikasinya setara atau lebih baik. Anak muda didorong untuk mandiri dan bekerja keras, hanya untuk menemukan bahwa ada batas-batas tak kasatmata yang ditarik oleh hierarki sosial yang mengakar. Crazy Rich Asians beresonansi karena ia memotret realitas ini dengan kejernihan yang tak nyaman: kelas sosial masih menentukan siapa yang diterima dan dihargai.
Akhir film memberi Rachel pengakuan sebuah kemenangan emosional yang memuaskan. Namun, resolusi itu menyisakan pertanyaan besar: mengapa penerimaan harus ditebus dengan pembuktian yang begitu luar biasa? Jawabannya terletak pada sistem yang memandang posisi sosial sebagai warisan, bukan capaian; pada budaya yang menilai orang dari “siapa keluargamu” alih-alih “siapa dirimu”. Selama asumsi-asumsi ini tak dipertanyakan, meritokrasi akan tetap menjadi cita-cita, bukan kenyataan.
Sebagai komedi romantis, Crazy Rich Asians memang menghibur. Tetapi sebagai cermin sosial, film ini mengajak refleksi lebih jauh. Ia menyingkap cara-cara halus kekuasaan bekerja melalui sopan santun, tradisi, dan “niat baik” untuk mempertahankan batas kelas. Di titik itulah film ini melampaui genre: bukan sekadar kisah cinta, melainkan peringatan bahwa cinta kerap diuji oleh standar yang tak pernah ia pilih.
Pertanyaan yang ditinggalkan film ini relevan di mana pun: apakah kita akan terus mengukur relasi dengan garis keturunan dan reputasi, atau berani menilai manusia dari pilihan dan tanggung jawabnya? Selama tembok-tembok kelas sosial dibiarkan berdiri, cinta akan terus diminta memenuhi syarat yang bukan miliknya.