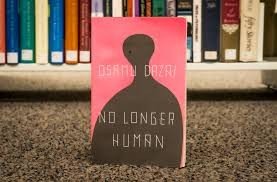Oleh: Mutia Salsabila (Pemerhati Bahasa dan Budaya)
Empat abad telah berlalu sejak William Shakespeare menulis Sonnet 130, tetapi kritik yang ia sampaikan terasa semakin relevan hari ini. Di tengah dunia yang dipenuhi citra sempurna, filter digital, dan tuntutan penampilan ideal, puisi ini hadir sebagai pengingat bahwa standar kecantikan sering kali dibangun di atas ilusi. Pertanyaannya sederhana, namun mengganggu: mengapa kita masih terjebak dalam standar kecantikan yang tidak realistis, padahal kritik terhadapnya telah disuarakan sejak lama?
Berbeda dari tradisi puisi cinta pada zamannya, Shakespeare memilih jalur yang tidak lazim. Ia menolak metafora hiperbolik yang kerap menyamakan perempuan dengan matahari, bunga, atau permata. Baris pembuka “My mistress’ eyes are nothing like the sun” bukanlah penghinaan, melainkan pernyataan sikap. Shakespeare menanggalkan bahasa pujian berlebihan untuk menghadirkan deskripsi yang jujur dan membumi. Kekasihnya tidak dipuja sebagai sosok sempurna, melainkan dicintai sebagai manusia nyata dengan keterbatasan fisik.
Pilihan estetika ini mengandung kritik sosial yang tajam. Pada masa Shakespeare, perempuan sering direduksi menjadi objek idealisasi dalam sastra. Tubuh dan wajah mereka disusun sesuai imajinasi maskulin tentang kesempurnaan. Dengan membalikkan konvensi tersebut, Sonnet 130 menyingkap kepalsuan di balik pujian yang terdengar indah, tetapi justru meniadakan kemanusiaan perempuan. Cinta, dalam puisi ini, tidak lahir dari pemujaan berlebihan, melainkan dari penerimaan.
Kritik itu beresonansi kuat dengan realitas hari ini. Standar kecantikan modern, meski dikemas dengan teknologi dan industri yang berbeda, masih bekerja dengan logika serupa. Media sosial menghadirkan wajah-wajah tanpa pori, tubuh tanpa lipatan, dan kulit tanpa cela. Filter, perawatan ekstrem, hingga prosedur kosmetik sering dipromosikan sebagai jalan menuju “kesempurnaan”. Perempuan, dan semakin banyak laki-laki, didorong untuk menyesuaikan diri dengan gambaran ideal yang sempit dan seragam.
Dalam konteks ini, Sonnet 130 dapat dibaca sebagai bentuk perlawanan kultural. Shakespeare tidak menertawakan kekasihnya, melainkan menertawakan standar itu sendiri. Ia menunjukkan bahwa bahasa cinta yang jujur justru lebih manusiawi daripada metafora yang dibuat-buat. Kejujuran ini menawarkan model relasi yang lebih sehat, relasi yang tidak menuntut tubuh ideal sebagai syarat untuk dicintai.
Puisi ini juga bekerja sebagai satire. Shakespeare menyadari bahwa pujian berlebihan sering kali lebih mencerminkan ego penyair dan tuntutan budaya daripada realitas orang yang dipuji. Satire tersebut relevan di era digital, ketika citra diri dibangun melalui kurasi visual yang ketat. Banyak orang merasa harus “memperbaiki” dirinya agar layak tampil dan diterima. Ketidaksempurnaan dipandang sebagai kegagalan personal, bukan sebagai bagian alami dari kemanusiaan.
Yang menarik, Sonnet 130 tidak berhenti pada kritik. Di bagian penutup, Shakespeare menegaskan bahwa cintanya tetap tulus dan bernilai, justru karena tidak didasarkan pada ilusi. Di sinilah pesan etis puisi ini menguat. Cinta yang sejati tidak membutuhkan standar yang mustahil. Ia bertumbuh dari pengakuan terhadap kenyataan, bukan dari penyangkalan atasnya.
Sebagai karya sastra klasik, Sonnet 130 membuktikan bahwa literatur tidak pernah sepenuhnya terlepas dari konteks sosial. Puisi ini menjadi cermin yang memantulkan kegelisahan lintas zaman. Ia mengajak pembaca untuk mempertanyakan narasi dominan tentang kecantikan dan untuk menyadari bagaimana standar tersebut membentuk cara kita memandang diri sendiri dan orang lain.
Membaca Sonnet 130 hari ini berarti membaca ulang hubungan kita dengan tubuh, cinta, dan kejujuran. Shakespeare seakan mengingatkan bahwa melawan standar kecantikan bukanlah sikap sinis terhadap keindahan, melainkan upaya mengembalikan keindahan pada maknanya yang paling manusiawi. Pada titik ini, pertanyaan yang perlu kita ajukan bukan lagi tentang siapa yang memenuhi standar, melainkan tentang mengapa standar itu terus kita pertahankan.