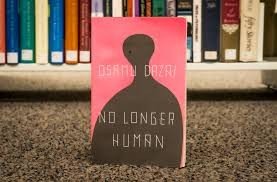Oleh: Allya Martiana Triwidyaningsih (Mahasiswi, Pemerhati Budaya Pop)
Cerita pendek kerap bekerja seperti ruang sunyi yang dipadatkan. Dengan batasan panjang, cerpen menuntut ketepatan pilihan kata dan disiplin emosi: apa yang ditampilkan harus berarti, apa yang disisakan harus beresonansi. “The Man Who Stole the Star” karya CA Limina, yang terbit di The Jakarta Post pada 2018, menjalankan prinsip itu dengan tenang namun menghantam. Cerita ini mengikuti Reza dan Ahmad, dua sahabat masa kecil yang dipisahkan ambisi dan dipertemukan kembali oleh nostalgia, kehilangan, serta penyesalan. Dunia yang dibangun sederhana, tetapi retaknya terasa nyata.
Mosi debat “The narrative reflects modern urban loneliness and spiritual emptiness” sempat menimbulkan keraguan: apakah kesepian dan kekosongan spiritual dapat dibaca tanpa dramatisasi? Diskusi justru membuka jalan pembacaan yang lebih jernih. Limina tidak menyuguhkan kesepian sebagai peristiwa besar; ia menyelipkannya dalam keputusan kecil, jarak emosional, dan cara pandang yang berubah.
Modernitas kerap dirayakan sebagai mesin mobilitas. Reza menjadi wajahnya: merantau, membangun kota, menegakkan reputasi, dan menata hidup yang terlepas dari akar masa kecil. Namun modernitas juga membawa keterputusan. Kalimat Reza, “I helped build this town. I’m not responsible for what happens afterward,” menandai jarak etis sekaligus emosional. Kota baginya adalah proyek, bukan rumah. “Bintang” dalam cerita bekerja sebagai metafora ambisi dan keberhasilan, cahaya yang diyakini mampu menebus masa lalu.
Masalahnya, keberhasilan itu berbiaya. Reza kembali dengan capaian, bukan dengan kedamaian. Ia menatap kampung halaman melalui lensa pekerja kota: tanah menjadi angka, kenangan menjadi potensi. Ketika Ahmad tiada akibat kecelakaan kerja, dialog Reza beralih dari percakapan menjadi monolog yang memantul pada udara. Kutipan penutup, tentang satu bintang yang tersisa, tentang rindu yang dijawab sunyi, menyelesaikan cerita tanpa keriuhan. Kesedihan tidak diucapkan dengan tangis; ia hadir sebagai jeda yang tak berjawab.
Di titik ini, Limina menampilkan potret kesepian urban yang subtil. Reza tidak sendirian secara fisik, tetapi terasing secara makna. Ia mengejar cahaya yang dingin: terang tanpa kehangatan. Kota menyilaukan, namun memudarkan relasi. Reza meraih “bintangnya,” tetapi kehilangan hal-hal yang membuat manusia utuh, kedekatan, perasaan memiliki, dan kesadaran spiritual.
Kekosongan spiritual dalam cerpen ini tidak diikat pada ritual atau doktrin, melainkan pada putusnya ikatan makna. Reza tidak lagi bertanya “untuk siapa” dan “mengapa,” hanya “bagaimana” dan “berapa.” Ketika Ahmad yang merupakan representasi akar, kesetiaan, dan kebersamaan menghilang, barulah kekosongan itu terdengar. Sunyi muncul bukan karena tiadanya suara, melainkan karena hilangnya alamat bagi suara itu.
Relevansi cerita ini dengan kehidupan urban masa kini terasa kuat. Kota menjanjikan kesempatan, tetapi sering memerangkap manusia dalam logika produksi yang menipiskan empati. Relasi menjadi transaksional, rumah menjadi titik singgah. Limina tidak menghakimi; ia mengamati. Kritiknya bekerja lewat kontras: cahaya kota versus gelap batin, kemajuan versus kehilangan.
Kekuatan cerpen ini terletak pada pilihan estetik yang menahan diri. Tidak ada khutbah, tidak ada penjelasan berlebih. Pembaca dibiarkan mengisi jeda, merasakan sunyi yang tidak berteriak. Dengan demikian, “The Man Who Stole the Star” melampaui kisah pertemanan dan nostalgia. Ia menjadi cermin bagi pengalaman urban yang kerap tak disadari: ketika manusia berjalan cepat menuju cahaya, tetapi lupa memeriksa apakah cahaya itu masih menghangatkan.
Kesepian urban dalam cerita ini bukan soal jumlah orang di sekitar, melainkan jarak dari makna-makna kecil yang membentuk hidup. Limina mengingatkan bahwa dalam perjalanan mengejar terang, manusia bisa kehilangan arah bahkan kehilangan cahaya yang semula dicari.