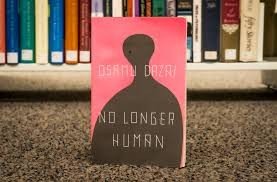Oleh: Hilman Mochammad Kahfi (Mahasiswa, Pembaca Aktif Karya Sastra)
Di tengah kehidupan modern yang dipenuhi konektivitas, perasaan terasing justru semakin sering hadir tanpa disadari. Media sosial, tuntutan profesional, dan ekspektasi sosial menciptakan ilusi kebersamaan, tetapi tidak selalu menghadirkan kedekatan emosional. Fenomena ini telah lama dibicarakan dalam kajian kesehatan mental, dan salah satu karya sastra yang menggambarkannya secara jujur adalah No Longer Human karya Osamu Dazai. Novel ini menghadirkan potret manusia yang gagal menyesuaikan diri dengan norma sosial, sekaligus memperlihatkan luka batin yang sering tersembunyi di balik wajah keseharian.
Tokoh utama dalam novel ini, Yozo Oba, hidup dengan rasa takut terhadap interaksi sosial. Ia merasa tidak memahami aturan tidak tertulis tentang bagaimana menjadi manusia seperti orang lain. Ketidakmampuan ini membuatnya mengembangkan strategi bertahan hidup berupa topeng sosial. Yozo tampil lucu, ramah, dan tampak mudah bergaul, seolah tidak memiliki masalah. Namun, di balik performa tersebut, ia menyimpan kehampaan dan keyakinan bahwa dirinya cacat sebagai manusia. Ia tidak merasa menjadi bagian dari dunia yang mengelilinginya.
Pengalaman Yozo dapat dibaca melalui teori dramaturgi Erving Goffman, yang memandang kehidupan sosial sebagai panggung pertunjukan. Dalam kerangka ini, individu memainkan peran tertentu demi diterima oleh masyarakat. Yozo adalah contoh ekstrem dari subjek yang sepenuhnya hidup di wilayah “front stage”. Ia mempertahankan citra yang diharapkan orang lain, sementara kehidupan batinnya terkurung di “back stage” yang tidak pernah tersentuh empati. Ketegangan antara peran sosial dan identitas personal inilah yang memperparah rasa keterasingan.
Selain itu, No Longer Human juga relevan dibaca melalui perspektif eksistensialisme, khususnya gagasan tentang alienasi dan absurditas hidup. Yozo mengalami krisis eksistensi karena tidak mampu menemukan makna dalam relasi sosial yang baginya terasa palsu. Dunia sosial hadir sebagai ruang yang menuntut kepatuhan, bukan pemahaman. Ketika individu tidak mampu atau tidak mau menyesuaikan diri, ia akan terdorong ke pinggiran. Novel ini memperlihatkan bagaimana tekanan untuk “menjadi normal” justru menghancurkan subjektivitas manusia.
Kritik terhadap norma sosial menjadi salah satu kekuatan utama novel ini. Masyarakat sering kali menuntut individu untuk berfungsi sesuai standar tertentu tanpa benar-benar mendengarkan kondisi batin mereka. Yozo tidak pernah diberi ruang untuk rapuh. Setiap tanda kelemahan dianggap kegagalan moral. Dalam konteks ini, keterasingan bukan semata masalah pribadi, melainkan hasil dari sistem sosial yang menolak perbedaan emosional dan psikologis.
Jika dikaitkan dengan kehidupan kontemporer, pengalaman Yozo terasa sangat dekat. Banyak orang modern hidup dengan citra yang harus terus dijaga. Di ruang kerja, seseorang dituntut tampil profesional dan stabil. Di media sosial, kebahagiaan sering dipentaskan sebagai bukti keberhasilan hidup. Keinginan untuk terlihat baik-baik saja membuat banyak individu menekan kecemasan, kesedihan, dan kelelahan emosional. Topeng sosial yang digambarkan Dazai puluhan tahun lalu kini hadir dalam bentuk unggahan, pencitraan, dan narasi kesuksesan.
Meski demikian, No Longer Human tidak sekadar menghadirkan keputusasaan. Novel ini membuka ruang refleksi tentang kemanusiaan yang rapuh. Dengan gaya narasi yang jujur dan getir, Dazai mengajak pembaca menatap sisi manusia yang jarang dibicarakan secara terbuka. Rasa asing, rasa tidak cocok dengan dunia, dan keinginan untuk menghilang bukanlah anomali, melainkan pengalaman yang mungkin dialami siapa saja.
Sebagai pembaca, novel ini dapat dibaca bukan sebagai pembenaran atas kehancuran diri, melainkan sebagai peringatan. Keterasingan sering hadir secara diam-diam, tersembunyi di balik tawa, kesopanan, dan rutinitas. No Longer Human mengingatkan bahwa empati sosial tidak cukup berhenti pada penampilan luar. Di balik sikap normal dan senyum sehari-hari, bisa saja tersembunyi luka batin yang tidak pernah benar-benar didengar.